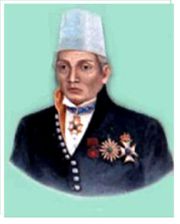RAY Kajoran - Keturunan (Inventaris)
Dari Rodovid ID
2
21/2 <1> ♀ Ratu Kulon II / Roro Oyi [Giri] 32/2 <1+?> ♂ Ki Ageng Wonosegoro [?]3
41/3 <3> ♂ Ngabehi Giring Wonojoyo [Wonosegoro]4
51/4 <4> ♂ Kyai Sutowijoyo [Wonojoyo]5
61/5 <5+?> ♂ Ki Ageng Wirorejo (Raden Tumenggung Wiraredja) [Sutowijoyo]6
71/6 <6> ♀ Kanjeng Ratu Kencana [Wiraredja]7
perkawinan: <2> ♀ Raden Ayu Pamogan [Majapahit]
perkawinan: <3> ♀ Kanjeng Raden Ayu Handoyo / Raden Ayu Adipati Anom (Ratu Kencana) [Cakraningrat]
perkawinan: <4> ♀ Ratu Kencanawungu / Raden Ayu Sukaptinah [Pakubuwono]
perkawinan: <5> ♀ Mas Ayu Rantansari Joyokartiko [?]
perkawinan: <6> ♀ Raden Retnodiningsih [Mangkuyudho III]
gelar: 29 September 1788 - 2 Oktober 1820, Surakarta, Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati Ing Ngalogo Abdur Rahman Sayyidin Panotogomo IV
wafat: 2 Oktober 1820, Surakarta
Awal Pemerintahan Nama aslinya adalah Raden Mas Subadya, putra Pakubuwana III yang lahir dari[[ permaisuri keturunan sultan Demak]]. Ia dilahirkan tanggal 2 September 1768 dan naik takhta tanggal 29 September 1788, dalam usia 20 tahun.
Pakubuwana IV adalah raja Surakarta yang penuh cita-cita dan keberanian, berbeda dengan ayahnya yang kurang cakap. Ia tertarik pada paham Kejawen dan mengangkat para tokoh golongan tersebut dalam pemerintahan. Hal ini tentu saja ditentang para pejabat Islam yang sudah mapan di istana.
Para tokoh Kejawen tersebut mendukung Pakubuwana IV untuk bebas dari VOC dan menjadikan Surakarta sebagai negeri paling utama di Jawa, mengalahkan Yogyakarta.
Peristiwa Pakepung Keadaan Surakarta semakin tegang. Para pejabat yang tersisih berusaha mengajak VOC untuk menghadapi raja. Pakubuwana IV sendiri membenci VOC terutama atas sikap residen Surakarta bernama W.A. Palm yang korup.
Residen Surakarta pengganti Palm yang bernama Andries Hartsinck terbukti mengadakan pertemuan rahasia dengan Pakubuwana IV. VOC mulai cemas dan menduga Hartsinck dimanfaatkan Pakubuwana IV sebagai alat perusak dari dalam.
VOC akhirnya bersekutu dengan Hamengkubuwana I dan Mangkunegara I untuk menghadapi Pakubuwana IV. Pada bulan November 1790 bersama mereka mengepung Keraton Surakarta. Dari dalam istana sendiri, para pejabat senior yang tersisih ikut menekan Pakubuwana IV agar menyingkirkan para penasihat rohaninya. Peristiwa ini disebut Pakepung.
Pakubuwana IV akhirnya mengaku kalah tanggal 26 November 1790 dengan menyerahkan para penasihatnya yang berpaham Kejawen untuk dibuang VOC.
Sikap terhadap Yogyakarta Atas prakarsa VOC, maka Pakubuwana IV, Hamengkubuwana I dan Mangkunegara I bersama menandatangani perjanjian yang menegaskan bahwa kedaulatan Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegaran adalah setara dan mereka dilarang untuk saling menaklukkan.
Meskipun demikian, Pakubuwana IV tetap saja menyimpan ambisi untuk mengembalikan Mataram-Yogyakarta ke dalam pangkuan Surakarta. Sejak tahun 1800 tidak ada lagi VOC karena dibubarkan pemerintah negeri Belanda. Sebagai gantinya, dibentuk pemerintahan Hindia Belanda yang juga dipimpin seorang gubernur jenderal.
Herman Daendels gubernur jenderal Hindia Belanda sejak 1808 menerapkan aturan yang semakin merendahkan kedaulatan istana. Dalam hal ini Pakubuwana IV seolah-olah menerima kebijakan itu karena ia berharap Belanda mau membantunya merebut Yogyakarta.
Pakubuwana IV juga pandai bersandiwara di hadapan Thomas Raffles, wakil pemerintah Inggris yang telah menggeser pemerintahan Hindia Belanda tahun 1811. Sementara itu Hamengkubuwana II (pengganti Hamengkubuwana I terkesan kurang ramah terhadap bangsa asing.
Pakubuwana IV memanfaatkan kesempatan itu. Ia saling berkirim surat dengan Hamengkubuwana II yang berisi hasutan supaya Yogyakarta segera memberontak terhadap penjajahan Inggris. Harapannya, Yogyakarta akan hancur di tangan Inggris.
Pihak Inggris lebih dulu mengambil tindakan. Pada bulan Juni 1812 istana Yogyakarta berhasil diduduki dengan bantuan Mangkunegara II. Hamengkubuwana II sendiri ditangkap dan dibuang ke Penang.
Persekutuan dengan Orang-Orang Sepoy Surat-menyurat antara Pakubuwana IV dan Hamengkubuwana II terbongkar. Pihak Inggris tidak menurunkan Pakubuwana IV dari takhta tapi merebut beberapa wilayah Surakarta.
Pakubuwana IV belum juga jera. Pada tahun 1814 ia bersekutu dengan kaum Sepoy dari India, yaitu tentara yang dibawa Inggris untuk bertugas di Jawa. Tentara Sepoy ini diajak Pakubuwana IV untuk memberontak terhadap Inggris, serta menaklukkan Yogyakarta yang saat itu dipimpin Hamengkubuwana III.
Persekutuan ini kandas tahun 1815. Sebanyak 70 orang Sepoy yang terlibat pemberontakan diadili pihak Inggris. Sejumlah 17 orang di antaranya dihukum mati, sedangkan sisanya dipulangkan ke India sebagai tawanan. Thomas Raffles juga membuang seorang pangeran Surakarta yang dianggap sebagai penghasut Pakubuwana IV.
Akhir Pemerintahan Pakubuwana IV masih menjadi raja Surakarta tanpa diturunkan Inggris. Sebaliknya, ia mengalami pergantian pemerintah penjajah, dari Inggris kembali kepada Belanda tahun 1816.
Pakubuwana IV meninggal dunia tanggal 2 Oktober 1820. Ia digantikan putranya yang bergelar Pakubuwana V.
Selain dikenal sebagai ahli politik yang cerdik, Pakubuwana IV juga terkenal dalam bidang sastra, khususnya yang bersifat rohani. Ia diyakini mengarang naskah Serat Wulangreh yang berisi ajaran-ajaran luhur untuk memperbaiki moral kaum bangsawan Jawa.
Pujangga besar Ranggawarsita mengaku semasa muda ia pernah belajar beberapa ilmu kesaktian kepada Pakubuwana IV. Ranggawarsita sendiri merupakan cucu angkat Pangeran Buminoto, adik Pakubuwana IV.8
171/8 <10+6> ♂ Bendoro Raden Mas Lamdani (Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumoyudho) [Pakubuwono IV]perkawinan: <8> ♀ Raden Ayu Sosrokusumo / Ratu Kencana [Martani]
perkawinan: <9> ♀ Ratu Mas / Kanjeng Ratu Ageng [?]
perkawinan: <10> ♀ Raden Ayu Dewakusuma [?]
perkawinan: <11> ♀ R Ayu Malayasari [Bratadiningrat - Banyumas]
gelar: 10 Februari 1820 - 5 September 1823, Surakarta, Bergelar Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwono V
wafat: 5 September 1823, Surakarta
Kisah Hidup Nama aslinya adalah Raden Mas Sugandi, putra Pakubuwana IV yang lahir dari permaisuri Raden Ayu Handoyo putri Adipati Cakraningrat bupati Pamekasan. Ia naik takhta pada tanggal 10 Februari 1820, selang delapan hari setelah kematian ayahnya.
Pakubuwana V juga dikenal dengan sebutan Sunan Sugih, yang artinya “Baginda Kaya”, yaitu kaya harta dan kaya kesaktian. Konon, ia pernah membuat keris pusaka dengan tangannya sendiri, bernama Kyai Kaget, yang berasal dari pecahan meriam pusaka Kyai Guntur Geni saat terjadinya pemberontakan orang Cina tahun 1740.
Pakubuwana V juga memerintahkan ditulisnya Serat Centhini berdasarkan pengalaman pribadinya semasa menjabat Adipati Anom. Yang menjadi juru tulis naskah populer ini ialah Raden Rangga Sutrasna.
Pakubuwana V hanya memerintah selama tiga tahun. Ia meninggal dunia pada tanggal 5 September 1823. Raja Surakarta selanjutnya adalah putranya, yaitu Pakubuwana VI, yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional.
SRI SUSUHUNAN PAKUBUWANA V, BUKAN HANYA RAJA dari Karaton Surakarta Hadiningrat, melainkan beliau juga seorang maecenas besar yang pernah dimiliki Indonesia. Meski kekuasaannya berlangsung sangat pendek (1820-1823), namun jasa dan gagasannya terukir panjang. Dari gagasan, dan tentu donasi beliau (yang bahkan telah dimulai ketika masih sebagai putra mahkota bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara ing Surakarta, seorang putra Kanjeng Susuhunan Pakubuwana IV), lahirlah pada awal abad 19 itu, Suluk Tambangraras yang kemudian lebih dikenal sebagai Serat Centhini. Serat Centhini, ditulis tahun 1815 oleh tiga pujangga Karaton Surakarta. Yakni, Ki Ngabei Ranggasutrasna, Raden Tumenggung Sastranegara, dan Ki Ngabei Sastradipura. Sebagai sebuah karya sastra, memenuhi syarat sebagai sebuah mahakarya yang memiliki pengaruh luas. Sampai banyak orang bisa berkomentar dan menilai, sekali pun sama sekali belum pernah membacanya, sampai hari ini. Begitu hebatnya ia, sampai-sampai karya ini muncul dalam banyak versi. Setidaknya ditengarai ada 12 versi Serat Centhini, dan itu sudah cukup menunjukkan kelasnya. Daerah tebanya begitu luas. Ia mengenai apa saja. Bukan hanya mengenai sastra atau seni, melainkan juga tentang adat-istiadat, obat-obatan, makanan dan minuman (jaman sekarang disebut kuliner), pengetahuan tentang hewan, tanaman, agama, sejarah, dan bahkan tentang seks. Tentang yang terakhir itulah, Serat Centhini antara lain dikenal luas. Karena Serat Centhini-lah karya sastra Jawa pada waktu itu, yang berbicara berterus-terang perihal seks. Penjabarannya, bukan hanya verbal tetapi kadang liar. Dalam Serat Centhini, juga dikisahkan bagaimana terjadi anal seks atau pun praktik homo-seksualitas. Dan bahkan, seks massal,... Pada bagian-bagian yang berkait dengan seks itu, konon Pakubuwana V sendiri yang turun tangan, menulis langsung. Itu terjadi setelah tiga penulisnya dirasa tidak memuaskannya. Tidak nges, dan kurang lugas. Kurang mak nyus, kata almarhum Prof. Dr. Umar Kayam (yang kemudian ditirukan atau dipopulerkan oleh pakar kuliner Bondan Winarno). Maka, Serat Centhini jilid 5 s.d 10 yang ditulis sendiri oleh sang Raja, sebagaimana kemudian bisa dibaca dalam kitab Serat Centhini sekarang ini. Ia mendapat banyak sebutan, sebagai karya korpus, monumental, sastra kanon yang begitu lengkap dan mencengangkan, karena cakupan isinya yang ensiklopedis, gaya bertuturnya, serta ketebalannya. Bayangkanlah, pada abad 19 itu, lahir karya sastra yang secara liris dan intens, ditulis sebanyak 12 jilid, dengan 722 pupuh tembang (jenis puisi Jawa). Satu pupuh tembang, tak jarang terdiri dari ratusan kuplet (bait), bahkan ada beberapa yang mencapai lebih dari 300 kuplet. Dan masing-masing kuplet terdiri antara 6 hingga 12 baris. Bisa dibayangkan, kepiawaian bahasa para penulisnya. Karena masing-masing pupuh tembang diikat oleh guru wilangan (jumlah suku kata yang terukur dan terhitung pasti), dan guru lagu (akhir suku kata masing-masing baris yang baku, untuk mendapatkan pola pantunnya). Karena itu, kata-kata dalam bahasa Jawa yang dipakai para penulisnya begitu lentur karena mengejar rima dan bunyi. Karena itu ketika Serat Centhini itu dilisankan (ditembangkan) siapa pun sepanjang mengetahui cara menyanyikan pupuh tembang itu, Centhini menjadi komunikatif, mudah untuk diapresiasi, dan mudah untuk disosialisasikan. Bahkan terbuka ditafsirkan dan punya kecenderungan bias, karena faktor pendengaran, pengertian, atau ingatan. Hal ini menjadi mudah terjadi, karena tembang sebagai sastra lisan yang jamak dilakukan pada waktu itu, terjadi dalam berbagai bentuk pertemuan banyak orang, ketika berada dalam upacara sunatan, pengantin, atau berbagai pertemuan-pertemuan rutin, yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok masyarakat, dalam berbagai waktu dan tempat. Karena itulah Centhini bisa muncul dalam banyak versi. Seperti Centhini Pegon. Centhini Jalalen. Centhini versi Madura. Dan lain sebagainya. Tidak dalam niat menyamakan, demikian pulalah ketika para sahabat Muhammad SAW hendak mengumpulkan hadist nabi, yang tentunya disampaikan secara lisan. Maka ketika hadist itu hendak dikumpulkan dan dituliskan, dibutuhkan para perawi hadis yang sahih, yang bisa menjamin tingkat kebenarannya. Apalagi, untuk kasus penulisan Alquran, yang dilakukan setelah nabi wafat. Demikian pula dengan kasus penulisan Injil, yang ditulis berdasar penuturan sahabat-sahabat Jesus seperti Lukas, Paul, Johannes dan lain sebagainya. Percontohan dalam karya sastra Indonesia, mungkin bisa ditemui pada novel “Para Priyayi” (1992) Umar Kayam, yang pembagian bab-nya ditulis menurut sudut pandang “aku” tokoh-tokohnya. Atau pada lahirnya novel kwarternarius “Bumi Manusia” (1980) Pramoedya Ananta Toer. Yang konon sebelum dituliskan, justeru dilisankan. Didongengkan terlebih dulu kepada sesama napi di Pulau Buru, untuk kemudian baru ditulis.
Serat Centhini (1815) berada dalam nasib berbeda, karena ia “hanya” sastra Jawa, yang tentu tidak segawat kasus penulisan kitab agama yang membutuhkan kesahihan dan kecanggihan. Demikian pula, ia bukan sastra teks Indonesia yang “mulia”, yang mempunyai para ahli kritiknya masing-masing. Sehingga perlu ada studi perbandingan atau studi kritis, sebagaimana dialami oleh Umar Kayam atau Pramoedya.perkawinan: <12> ♀ Bendoro Raden Ajeng Ngaisah [Mangkunegara I]
gelar: 17 Agustus 1858, Surakarta, Susuhunan Surakarta Ke-VII
wafat: 28 Desember 1861, Surakarta
Pemerintahan Pakubuwana VIII Nama aslinya adalah Raden Mas Kusen, putra Pakubuwana IV yang lahir dari istri selir bernama Mas Ayu Rantansari putri Ngabehi Joyokartiko, seorang menteri Surakarta. Ia dilahirkan pada tanggal 20 April 1789.
Pakubuwana VIII naik takhta pada tanggal 17 Agustus 1858 menggantikan adiknya (lain ibu) yaitu Pakubuwana VII yang meninggal dunia sebulan sebelumnya.
Pakubuwana VIII naik takhta pada usia lanjut, yaitu 69 tahun karena Pakubuwana VII tidak memiliki putra mahkota. Ia sendiri adalah raja keturunan Mataram pertama yang tidak melakukan poligami. Pemerintahannya berjalan selama tiga tahun. Pakubuwana VIII akhirnya meninggal dunia tanggal 28 Desember 1861.
Pakubuwana VIII digantikan putra Pakubuwana VI sebagai raja Surakarta selanjutnya, yang bergelar Pakubuwana IX.perkawinan: <13> ♀ Ratu Kencana [Pakubuwono III]
perkawinan: <14> ♀ Ratu Paku Buwono [Madura]
perkawinan: <15> ♀ Raden Ayu Retnodiluwih [Joyoningrat]
gelar: 14 Juni 1830 - 28 Juli 1858, Surakarta, Susuhunan Surakarta Ke-VII [1830–1858]
wafat: 28 Juli 1858, Surakarta
Nama aslinya ialah Raden Mas Malikis Solikin, putra Pakubuwana IV yang lahir dari permaisuri Raden Ayu Sukaptinah alias Ratu Kencanawungu. Ia dilahirkan tanggal 28 Juli 1796.
Pakubuwana VII naik takhta tanggal 14 Juni 1830 menggantikan keponakannya, yaitu Pakubuwana VI yang dibuang ke Ambon oleh Belanda. Saat itu Perang Diponegoro baru saja berakhir. Masa pemerintahan Pakubuwana VII relatif damai apabila dibandingkan masa raja-raja sebelumya. Tidak ada lagi bangsawan yang memberontak besar-besaran secara fisik setelah Pangeran Diponegoro. Jika pun ada hanyalah pemberontakan kecil yang tidak sampai mengganggu stabilitas keraton.
Keadaan yang damai itu mendorong tumbuhnya kegiatan sastra secara besar-besaran di lingkungan keraton. Masa pemerintahan Pakubuwana VII dianggap sebagai puncak kejayaan sastra di Kasunanan Surakarta dengan pujangga besar Ranggawarsita sebagai pelopornya. Hampir sebagian besar karya Ranggawarsita lahir pada masa ini. Hubungan antara raja dan pujangga tersebut juga dikisahkan sangat harmonis.
Pakubuwana VII juga menetapkan undang-undang yang berlaku sampai ke pelosok negeri, bernama Anggèr-anggèr Nagari. Selain itu, pada masanya dirilis pula pranata mangsa versi Kasunanan yang dimaksudkan menjadi pedoman kerja bagi petani dan pihak-pihak terkait dengan produksi pertanian. Pranata mangsa versi Kasunanan ini banyak dianut petani di wilayah Mataraman hingga diperkenalkannya program intensifikasi pertanian di awal 1970-an.
Pemerintahannya berakhir saat kematiannya pada tanggal 28 Juli 1758. Karena tidak memiliki putra mahkota, Pakubuwana VII digantikan oleh kakaknya (lain ibu) bergelar Pakubuwana VIII yang naik takhta pada usia 69 tahun.